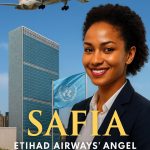Yogyakarta – suaraglobal.tv
Pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-5 Akademi Komunitas Negeri (AKN) Seni Budaya Yogyakarta pada 3 Juli 2025 jam 09.00 – 12.00 WIB di Kampus AKN Seni Budaya Yogyakarta Jl. Parangtritis No.364, Pandes, Panggungharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof. Dr. Suminto A. Sayuti Pidato Ilmiah dengan judul “Membangun Relasi Dialektis Resiprokal Melalui Jalan Seni Budaya”
AKN Seni Budaya Yogyakarta adalah sebuah lembaga Pendidikan tinggi seni budaya berstatus negeri yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma Satu (01) sampai Diploma Dua (D2), dengan berpedoman pada Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya dibentuk atas gagasan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Sultan Hamengku Buwono X) yang dimulai sejak tahun 2013, dengan surat usulan pendirian ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 412/5250, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Dikti dengan surat No.1266/E.E4/KL/2013, dan surat dari Dikti kepada Gubernur DIY, serta dengan diadakan visitasi lapangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Dikti sendiri pada tanggal 5 Juni 2014, dan hasil Rakor Akademi Komunitas Batch 3 dengan Perguruan Tinggi Pembina serta penyusunan RIP di Surabaya, tanggal 4-5 Juli 2013, maka Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya diijinkan untuk memulai melaksanakan program pendidikannya pada tahun akademik 2014-2015. Oleh karena itu sebelum memiliki satuan kerja sendiri, maka Akademi Komunitas Negeri Seni Dan Budaya Yogyakarta masih menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di bawah pembinaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sehingga untuk sementara ini, administrasi akademiknya masih berstatus sebagai mahasiswa ISI Yogyakarta.
AKN Seni Budaya Yogyakarta pada tahun 2020 telah lepas dari ISI Yogyakarta dengan Direkturnya Dr. Supadmo, M.Hum.(Dosen FSP ISI Yogyakarta) untuk periode 2020-2024. Pada periode berikut direkturnya Prof. Dr. Drs. Kuswarsantyo, M.Hum. (Dosen UNY). Direktur AKN Seni Budaya Yogyakarta Prof. Dr. Drs. Kuswarsantyo, M.Hum., Ketika ditemui awak Suara Global (3 Juli 2025) mengatakan Dies Natalis ke-5 ini mengangkat tema Mangesti Hayuning Kagunan yang artinya kita selalu menguri-uri sekaligus melestarikan lewat jalur pendidikan yang isinya adalah seni budaya.
Secara resmi Dies Natalis Ke-5 Akademi Komunitas Negeri (AKN) Seni Budaya Yogyakarta tertulis tanggal 3-5 Juli 2025. Sebetulnya sudah launching mulai 13 juni 2025. Nah di tanggal 3 Juli 2025 ini dalam Sedang Senat Terbuka menghadirkan Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, Guru Besar Universitas negeri Yogyakarta (UNY) untuk menyampaikan Pidato Ilmiah “Membangun Relasi Dialektis Resiprokal Melalui Jalan Seni Budaya”. Hal ini kami harapkan menjadi penyemangat, membuka cakrawala dalam pengelolaan institusi secara akademis agar lebih maju menyongsong masa depan secara realistis di era disruptip.
Prof. Dr. Suminto A. Sayuti lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Oktober 1956, sudah menerbitkan sejumlah buku, baik berupa kumpulan puisi, kumpulan esai, maupun buku teks kesastraan. Ia juga menulis artikel sastra-seni-budaya-pendidikan di berbagai media cetak dan jurnal. Selain dikenal sebagai penyair, kritikus, budayawan, akademisi, dan pendidik, Guru Besar Ilmu Sastra (1999) pada Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta ini juga suka menabuh gamelan Jawa, bermain wayang kulit, kethoprak, dan teater.
Pidato ilmiah setebal 17 halaman Prof Minto, panggilan akrab beliau, disarikan untuk memberikan pemahaman budaya di era disruptip. Ketika kata “budaya” diberi tambahan “bersama” sehingga membentuk frase “budaya bersama (common culture),” terdapat minimal dua penafsiran. Kata “bersama” berarti sesuatu yang terbagikan, tetapi juga memiliki makna yang terkait dengan sesuatu yang rendah, vulgar, dan mentah (kasar). Dalam pengertian kedua ini, istilah tersebut dapat dikaitkan dengan bahasa Latin, vulgus: orang-orang biasa. Oleh karena itu, kita dapat memainkan dua makna dari istilah “bersama.” Pertama, budaya merupakan suatu hal yang bersifat terbagikan dan integratif. Kedua, budaya merupakan suatu hal yang rendah, vulgar, dan mentah, sehingga memerlukan arahan dan bimbingan untuk membuatnya tinggi dan halus. Pertanyaannya, apakah secara faktual memang ada budaya bersama, atau, apakah seharusnya ada budaya bersama.
Budaya bersama mengasumsikan budaya yang koheren, atau ideologi yang dominan, yaitu budaya yang memainkan peran penting dalam mempertahankan tatanan, integrasi, dan kohesi sosial. Hal ini perlu dipisahkan dari pertanyaan kedua, yang berkembang dalam bidang teori seni-budaya dan kajian budaya, tentang nilai atau perlunya memiliki budaya bersama. Kita pun mendapatkan rentang posisi yang tipikal, yang menekankan bahwa budaya bersama telah eksis di masa lalu, tetapi kini sedang dalam proses dihancurkan oleh budaya konsumen massal. Oleh karena itu, harus dicari cara untuk merevitalisasi tradisi kultural tersebut. Alternatifnya, budaya bersama dapat diciptakan melalui pendidikan budaya yang pada akhirnya akan mencapai penghapusan residu budaya yang vulgar. Dalam kaitan ini, beberapa solusi selalu dimungkinkan, sehingga budaya bersama selalu berpeluang untuk dilestarikan, dikembangkan, diberdayakan, dan dibina, yang salah satu manifestasinya berupa karya-karya artistik, apapun bentuk dan genrenya.
Meningkatnya minat budaya dalam berbagai disiplin, terutama humaniora, pada hakikatnya menunjuk pada gerakan di luar budaya, yang dipahami secara sempit, baik sebagai “ke-seni-an” maupun sebagai sesuatu yang relatif stabil dan terbagi. Karenanya, norma, nilai, dan keyakinan pun tidak bermasalah, yakni sebagai perekat hubungan sosial. Oleh karena itu, upaya serius yang dilakukan secara sistematis diperlukan secara melembaga. Untuk apa? Untuk memetakan berbagai dimensi budaya, dan hubungan antara budaya dan masyarakat.
Prof Minto pun menyebut tokoh-tokoh dunia untuk memahamkan budaya itu. Margaret Archer (1988) menelusuri asal-usul mitos integrasi budaya yang memahami budaya sebagai seperangkat untaian yang koheren, yang menyatu menjadi satu kesatuan estetis yang dikapsulkan dalam istilah Zeitgeist dan Weltanschauung, yang menekankan kesatuan jiwa zaman dan pandangan-dunia. Sorokin (1957) menegaskan bahwa kita dapat menemukan “integrasi yang-bermakna-secara-logis,” yakni pola keseragaman yang memungkinkan kita untuk menghubungkan komponen-komponen individual yang masih kacau secara bersama-sama. Tesis ini dikenal sebagai “budaya bersama” dalam fungsionalisme Talcott Parsons (1951; 1961). Parsons menekankan bahwa seperangkat nilai sentral yang koheren (yakni, sistem budaya) bertindak sebagai unsur normatif berpola, yang menjamin keterpaduan dan keteraturan interaksi. Asumsi bahwa seperangkat nilai bersama secara fungsional diperlukan untuk mendorong konsensus normatif yang penting untuk memastikan tatanan sosial.
Intinya, budaya bersama dipertahankan atau ditransformasikan menjadi paham ideologi dominan, yakni sebagai sesuatu dipaksakan oleh sekelompok orang kepada orang lain. Masyarakat tidak mereproduksi dirinya sendiri, baik melalui budaya bersama maupun melalui ideologi dominan. Sistem nilai yang terbagi dan atau ideologi dominan dalam feodalisme, kapitalisme-awal abad ke-19, dan kapitalisme mutakhir abad ke-20 (Abercrombie, N., Hill, S. and Turner, B.S., 1980).
Jika nilai-nilai bersama sulit dipertahankan dalam kekompleksan masyarakat yang terdiferensiasi dengan tingkat pembagian kerja yang tinggi, mungkinkah hal-hal tersebut dapat dihidupkan kembali pada kesempatan-kesempatan tertentu, yang dapat menimbulkan perasaan bahwa masyarakat telah menjadi satu komunitas nasional yang bersatu? Durkheim berpendapat bahwa yang sakral tidak hilang dalam masyarakat modern, dan bahwa ada banyak contoh di luar situasi agama yang ketat, yang di dalamnya simbol dan ritual sakral digunakan untuk membangkitkan pengalaman emosional yang intens, yang memecah jarak sosial antar-orang (.Alexander, J.C. 1988). Peristiwa-peristiwa seperti itu, karena kualitasnya yang terisolasi dan tertutup dari kehidupan sehari-hari, disebut sebagai momen-momen liminal (Turner, V.W. 1969). Dalam kaitan ini, Shils and Young (1953) menyatakan bahwa hal itu merupakan sebuah tindakan “persekutuan nasional,” yang mengintegrasikan semua orang ke dalam tatanan sosial yang bermoral. Lalu kita pun menjadi ingat akan konsep bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang, seperti dinyatakan oleh Anderson (1983).
Hubungan antara seni-budaya dan kondisi sosial bersifat dialektis-resiprokal. Artinya, keduanya berada dalam posisi saling tergantung satu sama lain secara berkelanjutan. Masyarakat bisa saja mengalami perubahan akibat seni-budaya yang dihasilkannya. Dalam kaitan ini, di satu sisi, seni-budaya berhadapan dengan struktur yang mengandaikan karakteristik tertentu, dan di sisi lain, setiap perubahan di dalam satu bidang sosial terkait erat dengan perubahan di bidang lain. Artinya lebih lanjut, perubahan dalam sistem sosial akan mengacu pada asal-muasal terjadinya perubahan. Oleh karena itu, untuk mengekspresikan dan merepresentasikannya secara artistik, gambaran-gambaran pada kedua sisi tersebut saling memantulkan satu sama lain dalam pembiasan yang tidak mengenal akhir.
Dalam konteks tersebut, “pembacaan” seni-budaya, dalam arti perburuan makna, kita serupa berada di aula cermin. Di samping sebagai ekspresi individual, seni-budaya pun tidak hanya refleksi, tetapi juga refraksi kondisi sosial. Terjadilah perebutan posisi kekuatan sosial dan kekuatan artistik yang bersifat kompetitif. Multiplikasi dan intensifikasi yang berkesinambungan menjadi sebuah peristiwa yang tak terelakkan, menjadi kesibukan tanpa henti dalam perebutan makna, yang dengannya dialektika antara kondisi sosial dan seni-budaya terbentuk secara resiprokal.
Dialektika tersebut bermula dari adanya suatu kesatuan yang di dalamnya terjadi perpecahan dan atau ketidakselarasan, sehingga menimbulkan kontradiksi, yang bisa saja berupa konflik motif yang tidak bisa direkonsiliasikan. Bisa saja interaksi yang sejak awal mengandaikan dualitas prinsip, bergerak satu sama lain dalam arah yang berlawanan. Dalam tatanan artistik, muncul kecenderungan-kecenderungan kontradiktif yang mengarah pada konflik. Akan tetapi, pada tahap perkembangan berikutnya, muncul kecenderungan yang mengarah pada rekonsiliasi dan pada penyelesaian antitesis yang ada. Hubungan antara kondisi sosial dan seni-budaya dalam beberapa hal seperti hubungan antara tubuh dan jiwa kita: keduanya tidak bertentangan, keduanya juga tidak bisa selalu harmonis. Oleh karena itu, perkembangan dialektis seni-budaya itu bisa beragam. Ia tidak selalu berangkat dari pertentangan antara kepentingan sosial dan kepentingan artistik. Ia merupakan hasil konflik intensi artistik, masalah, kemungkinan solusi, dan sarana representasi. Singkatnya, perkembangan kondisi sosial hanya memberikan dorongan, tetapi tidak menimbulkan kontradiksi di antara seni-budaya dan masyarakat. Sikap antitesis bukanlah antagonisme, dan interaksi bukanlah perselisihan dialektis. Antagonisme terjadi, baik di dalam masyarakat maupun di dalam seni-budaya, tetapi tidak ada antagonisme antara masyarakat dan seni-budaya.
Penciptaan karya seni-budaya bergantung pada proses sosio-historis sejumlah faktor yang beraneka ragam, seperti alam, budaya, waktu, dan tempat. Tak satu pun hal tersebut yang menegaskan dirinya secara konsisten dalam pengertian yang sama. Masing-masing faktor memperoleh makna tertentu sesuai dengan konteks tempat ia muncul berikut faktor-faktor pembangun lainnya. Faktor-faktor yang terlibat dalam tindakan artistik-kreatif atau reseptif memperoleh karakter konkretnya hanya dengan cara faktor-faktor tersebut membatasi diri satu sama lain. Apabila diukur dengan totalitas pengalaman estetis-artistik, faktor-faktor tersebut hanyalah sebuah abstraksi. Tidak peduli seberapa besar perannya dalam formasi sebuah konsep estetis-artistik, tidak ada satu faktorpun yang menunjukkan kualitas khusus yang membuat suatu struktur menjadi sebuah karya seni-budaya.
Komponen suatu keseluruhan yang bersifat estetis-artistik, baik yang merupakan tujuan penciptaan maupun yang berupa pengalaman subjektif, sebagian termasuk dalam fenomena natural dan sebagian lagi termasuk dalam fenomena budaya, sosial, dan sejarah yang dapat berubah. Jika kita mengutamakan potensi alam dalam proses budaya, kita mengubah asal-usul struktur budaya menjadi suatu “proses alam yang misterius,” seperti dikatakan oleh Hauser (1982). Jika kita mengutamakan kesadaran, kita hanya menciptakan sebuah monster tanpa konten. Bagi kesadaran kreatif, sifat pasif dan buta sama misteriusnya dengan kesadaran spontan dari sudut pandang alam. Kaum idealis menyerah di hadapan kekuatan hukum alam yang tak tertahankan, sama seperti kaum realis meletakkan tangannya ketika dia membiarkan pikiran berkuasa tanpa hambatan dan tanpa syarat.
Setiap kreator yang secara historis konkret, yang berpikir dan bertindak, menemukan dirinya sendiri dalam lingkungan yang nyata, temporal, dan ditentukan secara lokal dan objektif. Potensi batinnya selalu terkait dengan serangkaian kondisi eksternal. Akan tetapi, hal tersebut tidak menandakan bahwa faktor-faktor dinamis proses sejarah, misalnya saja, hanya menjadi sekedar faktor pelengkap, atau bahwa faktor-faktor tersebut melestarikan sifatnya sendiri sambil mempengaruhi satu sama lain. Di dalam prosesnya, faktor-faktor tersebut mengalami perubahan yang mendasar, karakter yang tampaknya konstan menjadi dinamis dan mengambil karakteristik sesuai dengan keadaan perkembangan yang terjadi, sementara komponen-komponen yang pada hakikatnya dapat diubah, sampai batas tertentu menjadi tidak dapat diubah dan diobjektifikasi, dan akhirnya membentuk struktur otonom yang membebaskan diri dari akar-akar awal-mula dan kondisi-kondisi eksistensinya.
Unsur-unsur realitas yang statis menjadi faktor-faktor pembentuk pengembangan sejarah hanya dalam bentuk yang sesuai dengan kemungkinan fungsional tertentu. Sarana yang diciptakan manusia untuk pengelompokan sosial dan pembentukan budaya, konvensi, dan institusi, norma dan nilai-nilai, aturan perilaku dan kaidah yang mengatur pemikiran, kecenderungan gaya dan bentuk ekspresi, berubah menjadi prinsip tegas yang menentang spontanitas murni dan kebebasan individu.
Setiap tahapan proses estetis-artistik, secara mendasar mengandung tahapan berikutnya. Bahkan, jika hal itu hanya terlihat pada akhir proses yang dimaksud, setiap lapisan struktur bentuk estetis-artistik mengungkapkan maknanya hanya dalam hubungannya dengan strata lainnya. Keberhasilan karya seni-budaya tetap menjadi pertanyaan terbuka. Unsur-unsur yang menentukan nilai kualitatif sebuah karya seni-budaya hampir selalu berada dalam keseimbangan yang tidak stabil. Oleh karena itu, kita sering bertanya apakah keberhasilan tersebut merupakan hasil upaya dan penguasaan atas hal itu, ataukah hanya merupakan keberuntungan dan kebetulan atasnya.
Di atas segalanya, relasi dialektis-resiprokal dalam seni-budaya adalah hubungan antara bentuk dan konten, bukan hanya karena adanya perubahan dalam satu elemen yang membawa perubahan pada elemen lainnya, melainkan juga karena keduanya tidak dapat dipikirkan tanpa relasi dialektis-resiprokal satu sama lain. Artinya, kita tidak bisa mengatakan apa yang harus dibentuk tanpa memikirkan apa yang harus dibentuk dan sesuatu itu sedang dibentuk. Hanya ketika kita sadar akan kehadiran faktor-faktor tersebut dan tetap sadar akan ketidakterpisahannya, kita pun dapat memahami bahwa seni-budaya terdiri atas ketegangan dan pelepasan ketegangan, antitesis dan rekonsiliasi, diferensiasi dan integrasi. Karya seni-budaya adalah wahana dan hasil interaksi antara ekspresi dan isi pengalaman, yang selalu diperbaharui, dibedakan, dan diperdalam.
Pada awalnya kita berurusan dengan dua peristiwa yang berubah suatu kompleksitas yang pada dasarnya tidak dapat dipecahkan. Namun, jika kita menjelaskan relasi tersebut dengan mengatakan bahwa bentuk “berubah menjadi” isi atau sebaliknya, kita pun menggunakan bentuk ekspresi yang murni metaforis. Dengan menggunakan metafora, kita tidak mengatakan apa pun tentang proses yang lebih tepat atau lebih mudah dipahami. Keduanya berkembang selangkah demi selangkah sebagai solusi masalah yang tak terpisahkan, yakni masalah yang mereka tetapkan satu sama lain. “Isi keseluruhan” tidak lebih mapan sejak awal dibandingkan dengan “bentuknya.” Keduanya merupakan hasil yang secara teoretis yang dapat dibagi-bagi tentang sebuah proses yang secara praktis terpadu.
Uraian komprehensif perihal seni budaya secara akademis akan memperteguh keilmuan di AKN Seni Budaya Yogyakarta dibawah kepemimpinan Prof. Dr. Drs. Kuswarsantyo, MHum., akan semakin tercerahkan, dinamis dalam perkembangan zaman di era global ini. Setidaknya Prof. Dr. Suminto A. Sayuti via pidato ilmiahnya semakin tunjukkan arah yang benar di “Jalan Budaya” dalam koridor numenklatur keilmuan seni budaya. Hal ini akan berdampak positip dalam tumbuh-kembang AKN Seni Budaya Yogyakarta.
Wakil Direktur AKN Seni Budaya Yogyakarta, Bapak Kartiman, M.Sn. menjelaskan rangkaian acara Dies ke-5. Tanggal 13 Juni 2025 jam 07.30-10.00 WIB Senam Sehat. Tanggal 22 Juni 2025 Pengabdian Masyarakat oleh prodi Kriya Kulit. Tanggal 3 Juli 2025 jam 09.00 – 12.00 WIB, Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-5 Akademi Komunitas Negeri (AKN) Seni Budaya Yogyakarta menghadirkan Prof. Dr. Suminto A. Sayuti Pidato Ilmiah dengan judul “Membangun Relasi Dialektis Resiprokal Melalui Jalan Seni Budaya”. Dilanjutkan Niti Laku ke Makam Raja Kota Gede. Tanggal 4 Juli 2024 Bakti Sosial, Tanggal 5 Juli 2025 Bazar Kreatif-UMKM jam 08.00-16.00 WIB., Podjok Kreatif Tatah Sungging “Demonstrasi Proses Tatah Sungging:, jam 08.00=16.00 WIB; Lomba Karawitan Tradisional Gagrak Yogyakarta Jam 08.00 WIB. Sarasehan Budaya tema Menggali Nilai Kearifan Lokal Sebagai Inspirasi Pengembangan Kreativitas Menuju Pentas Global, Narasumber Den Baguse Ngarso (Drs. Susilo Nugroho), dan Prof. Dr. Drs. Kuswarsantyo, MHum. Dan malam puncaknya adalah pentas kesenian, salah satunya akan dimeriahkan bintang tamu penyanyi Woro Widowati. Tulisan ini kado Istimewa untuk Mas Prof Minto, salam sehat slalu dan buat Mas Prof Kuswarsatyo selamat memimpin AKN Seni Budaya Yogyakarta yang ultah ke-5. (Nur Iswantara).